
[Operation Decisive Storm] Ketika Israel Bersorak Saksikan Koalisi Arab Serang Yaman

Daerah Yaman yang lebih luas dikendalikan oleh kelompok pemberontak bersenjata daripada pemerintah pusat. (wikimedia).
Pada bulan Maret – April 2015, para
pemimpin Zionis Israel sedang bersukacita. Penyebabnya tak lain dan
tidak bukan adalah operasi militer koalisi sepuluh negara pimpinan Arab
Saudi untuk menghantam milisi al Khauthi di Yaman. Operasi itu bernama
“Operasi Badai Tegas” alias ‘Amaliyah ‘Ashifah al Hazm atau Operation Decisive Storm.
Dinamakan demikian, barangkali untuk
menegaskan kepada dunia, terutama milisi al Khauthi, bahwa operasi kali
ini tidak main-main. Bila milisi al Khauthi dan siapa pun yang
mendukungnya berani macam-macam, misalnya mengancam keamanan
negara-negara Teluk, maka mereka akan disikat dengan tegas oleh operasi
yang bagaikan badai besar bergulung-gulung.
Israel Merasa Tak Khawatir
Sebagai catatan, daratan Yaman di Jazirah Arabia berbatasan langsung dengan Saudi di sebelah utara, dan Oman di sebelah timur.
Meskipun operasi ini bernama Badai Tegas,
namun koalisi militer sepuluh negara ini justeru disambut Zionis Israel
dengan tempik sorak-sorai. Ya, mereka bisa menyaksikan pesawat tempur
koalisi menyerang sasaran-sasaran militer al Khauthi sambil minum kopi
di pagi hari. Santai dan nyaman.
Marilah kita simak tulisan kolomnis Yahudi Zvi Bar’el di media Israel Haaretz
edisi 30 Mei lalu. Katanya, sejumlah negara Arab sedang membentuk
sebuah kekuatan (koalisi) militer yang besar nan kuat dan, untuk pertama
kalinya, Israel tidak merasa khawatir. ‘‘Bukan hanya tidak khawatir,
tapi sebenarnya Israel juga gembira,’’ tulis Bar’el.

Perang
konflik antara Sunni vs. Syiah mirip ketika terjadi perang konflik
Kristen antara Katolik dan Protestan di Irlandia Utara di era 80-90an.
Semua agama diadu domba.
Menurut Zvi Bar’el, selama beberapa
generasi strategi pertahanan Israel didasarkan pada satu fokus, yaitu
untuk menangkal setiap koalisi militer Arab ketimbang militer
negara-negara Arab secara individu.
Namun, lanjutnya, Israel justeru melihat
koalisi yang sekarang sebagai elemen yang tak terpisahkan dari kebijakan
pertahanan Israel sendiri. Bahkan meskipun tidak terlibat dalam koalisi
itu, Israel telah mengambil keuntungan dari koalisi militer Arab itu.
Hal yang sama dinyatakan pengamat Israel lainnya, Prof Eyal Zisser. Dalam makalahnya di media Israel Hayom (Israel Today) pada awal April 2015 lalu, ia mengatakan koalisi militer pimpinan Saudi itu adalah ‘sesuatu yang menggembirakan’.
The Jewish Press yang terbit di
Amerika Serikat pekan lalu menyebutkan alasan mengapa Israel menyambut
dengan suka cita terhadap koalisi bentukan Arab Saudi tersebut.
Menurut media yang meyuarakan kepentingan
Yahudi itu, koalisi militer Arab untuk menyerang Israel yang dulu
pernah dibentuk sejak 65 tahun lalu, kini telah dihidupkan kembali.
Namun, kali ini bukan untuk menyerang Israel, tapi untuk membendung pengaruh Syiah di Jazirah Arabia.
‘‘Negara-negara Arab Sunni yang menentang Arab Spring adalah mereka yang kini memimpin perang melawan pengaruh Syiah di Timur Tengah,’’ tulis The Jewish Press.
The Arab Spring atau al Rabi’ al ‘Araby adalah revolusi rakyat Arab untuk menentang penguasa diktator otoriter yang berlangsung sejak empat tahun lalu.
Arab Berubah: Palestina bukan lagi prioritas utama bagi bangsa-bangsa Arab dan umat Islam
Kolomnis dan wartawan senior Mesir, Fahmi Huwaidi, sepakat dengan pandangan The Jewish Press. Dalam media Aljazeera.net pada 08/04/2015 lalu, ia menyatakan kawasan Timur Tengah kini memang sedang berubah.
Apalagi bila dibandingkan dengan tahun-tahun 1950-an hingga 1970-an. Tahun-tahun ketika Liga Arab atau Arab League dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) didirikan.
Waktu itu salah satu tujuan utama dari
pendirian kedua organisasi atau lembaga itu adalah membantu perjuangan
bangsa Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan di tanah airnya
sendiri.
 Tanah
air yang telah dighasab oleh Zionis Israel. Namun, kini nasib bangsa
Palestina bukan lagi prioritas utama bagi bangsa-bangsa Arab dan umat
Islam.
Tanah
air yang telah dighasab oleh Zionis Israel. Namun, kini nasib bangsa
Palestina bukan lagi prioritas utama bagi bangsa-bangsa Arab dan umat
Islam.
Walau iya pun, sudah bukan prioritas, bahkan bisa jadi semuanya hanya sandiwara belaka.
Mengutip Huwaidi, ada dua perubahan mendasar yang terjadi pada bangsa-bangsa Arab:
Pertama,
para pemimpin Arab kurang atau bahkan tidak peduli lagi pada nasib
bangsa Palestina. Suasana politik, keamanan, dan bahkan kebatinan
bangsa-bangsa Arab sekarang ini bahwa musuh utama mereka adalah pengaruh
Syiah dan bukan lagi Zionis Israel.
Kedua,
kekhawatiran terhadap pengaruh Syiah telah mengakibatkan konflik yang
tadinya bernuansa politik kini berubah menjadi konflik antarmazhab atau
paham keagamaan. Tepatnya antara Sunni dan Syiah. Konflik yang demikian
bisa saja melampaui batas-batas negara Arab dan merembet ke
negara-negara Islam (mayoritas berpenduduk Muslim) seantero jagad dunia, dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun.
‘‘Hal inilah yang menenangkan Zionis Israel dan memunculkan rasa suka cita,’’ ujar Huwaidi.
Contoh lain mengenai perubahan
negara-negara Arab yang menguntungkan Zionis Israel adalah dalam kasus
Mesir. Menurut Mohammad al Minsyawi, pakar politik tentang Amerika dan
direktur di Lembaga al Shuruq di Washington, selama puluhan
tahun ‘akidah’ atau doktrin militer Angkatan Bersenjata Mesir adalah
‘musuh utama mereka adalah Zionis Israel’.
Namun, lanjut al Minsyawi, doktrin tersebut kini sudah tidak banyak dibicarakan lagi di kalangan militer Mesir.
Hal ini bisa terjadi, katanya seperti dikutip Aljazeera.net, adalah bentuk dari pengaruh Gedung Putih dari satu presiden ke presiden lainnya.
Pengaruh yang acap kali dibungkus dalam bentuk bantuan militer Washington ke Kairo.
Mesir hingga kini dianggap sebagai salah
satu negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Baik dari segi jumlah
penduduk, politik, sosial/agama maupun militernya. Bahkan militer Mesir
kini merupakan yang paling kuat di antara negara-negara Arab lainnya.
Ada empat rambu yang selalu digariskan AS dalam memberikan bantuan persenjataan/militer ke Mesir, yaitu:
- Untuk memerangi teroris,
- Menjaga perbatasan,
- Mengawal serta menjaga keamanan laut, dan terakhir
- Memelihara keamanan Sinai.
Menurut al Minsyawi, senjata bantuan dari
Amerika tidak mungkin dipergunakan untuk menghadapi lawan-lawan yang
tidak didukung Gedung Putih. Artinya, peralatan militer AS, termasuk
persenjataannya, tidak mungkin digunakan untuk membantu bangsa Palestina
menyerang Israel.
Perubahan berikutnya yang juga disambut
dengan suka cita oleh Zionis Israel adalah beralihnya peta kekuatan di
negara-negara Arab. Terutama menyangkut kekuatan ekonomi, militer, dan
kemudian politik.
Negara-negara Teluk pada saat itu bisa
dikatakan hanyalah anak bawang. Kini negara-negara Teluk yang justru
menjelma menjadi kekuatan utama Liga Arab, selain Mesir.
Salah satu contoh pengaruh negara-negara
Teluk, terutama Arab Saudi, adalah pembentukan koalisi militer untuk
menyerang milisi al Khauthi di Yaman. Dengan pengaruh politik dan
ekonominya, Arab Saudi telah berhasil menjadikan isu keamanan negaranya
menjadi masalah keamanan Teluk dan bahkan Liga Arab.
Mengutip pandangan Fahmi al Huwaidi, Liga Arab sekarang ini sebenarnya adalah Liga Teluk
(Dewan Kerja Sama Teluk/Majelis at Ta’awun li Duali al Khalij al
‘Arabiyah). Pengaruh negara-negara Teluk yang kuat tentu akan
menguntungkan Israel. Sebab, negara-negara yang tergabung dengan Dewan Kerja Sama Teluk selama ini dikenal dekat dengan Barat/AS, sementara Barat adalah pendukung utama eksistensi Zionis Israel.
Semua perubahan yang terjadi di
negara-negara Arab itulah yang kemudian disambut Zionis Israel dengan
suka cita. Sebaliknya, kasihan pada nasib bangsa Palestina.
Inikah Penyebab Arab Takut Lawan Israel?
Melihat serangan koalisi Arab Saudi
terhadap pemberontak Houthi di Yaman, memunculkan beragam pertanyaan.
Koalisi tersebut lebih memilih menyerang Houthi yang berafiliasi ke
Syiah Iran, ketimbang membungihanguskan Israel penjajah sejati. Lantas,
benarkah ketidakberanian Arab terhadap Israel itu dipicu trauma atas
kekalahan mereka perang melawan Israel sepanjang sejarah?
Sejarah mencatat, Arab harus menelan
kekalahan terus menerus melawan Israel. Dalam Perang Arab-Israel
Pertama, menyusul pendirian negara Israel 14 Mei 1948 di bawah pimpinan
David Ben Gurion, aliansi negara Arab takluk di hadapan Israel.
Dalam perang yang berlangsung selama
hampir 10 bulan itu (sejak 15 Mei 1948 hingga 10 Maret 1949—Red),
pasukan Yordania, Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, dan Arab Saudi bergerak
ke Palestina untuk menduduki daerah-daerah yang diklaim sebagai wilayah
‘negara Israel’. Ada sekitar 45 ribu tentara yang dikerahkan oleh
negara-negara Arab tersebut pada waktu itu.
“Sementara, di pihak Israel sendiri
awalnya hanya diperkuat oleh 30 ribu prajurit, namun pada Maret 1949
meningkat jumlahnya menjadi 117 ribu tentara,” ungkap Yoav Gelber dalam
buku Palestine 1948: War, Escape and the Emergence of the Palestinian Refugee Problem.
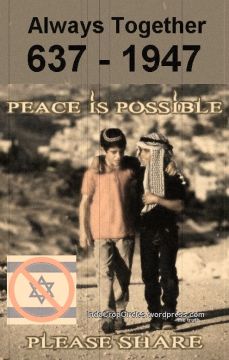 Perang
Arab-Israel Pertama berakhir dengan kekalahan di pihak negara-negara
Arab. Menurut catatan, jumlah tentara Arab yang gugur mencapai 7.000
orang.
Perang
Arab-Israel Pertama berakhir dengan kekalahan di pihak negara-negara
Arab. Menurut catatan, jumlah tentara Arab yang gugur mencapai 7.000
orang.
Perang itu juga menewaskan 13 ribu warga
Palestina. Di samping itu, berdasarkan hasil penghitungan resmi PBB, ada
711 ribu orang Arab yang menjadi pengungsi selama pertempuran
berlangsung.
Sebagai akibat dari kemenangan Israel
tersebut, setiap orang Arab yang mengungsi selama Perang Arab-Israel
Pertama, tidak diizinkan untuk pulang ke kampung halaman mereka yang
kini sudah diklaim Zionis sebagai wilayah negara Israel.
“Oleh karenanya, para pengungsi Palestina
yang kita jumpai hari ini adalah keturunan dari orang-orang Arab yang
meninggalkan tanah air mereka ketika terjadinya perang 1948-1949,” tutur
Erskine Childers lewat tulisannya, The Other Exodus The Spectator, yang dipublikasikan dalam buku The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict,(1969).
Perang Arab-Israel kembali meletus ketika
Mesir melakukan nasionalisasi terhadap Terusan Suez pada 1956.
Kebijakan yang digawangi oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser itu
mendorong Israel untuk menginvasi Semenanjung Sinai, sehingga
menyebabkan peristiwa yang dikenlan sebagai ‘Krisis Suez’.
Tak lama berselang, pasukan Inggris dan
Prancis juga mendarat di Pelabuhan Suez. Keikutsertaan dua negara Eropa
itu dalam konflik tersebut seolah-olah untuk memisahkan pihak yang
bertikai. Namun, motivasi mereka sebenarnya pada waktu itu hanya untuk
melindungi kepentingan investor di negara-negara yang terkena dampak
nasionalisasi Terusan Suez oleh Mesir.
Perang Arab-Israel yang kedua ini
berakhir dengan kesepakatan damai. Mesir setuju untuk membayar jutaan
dolar kepada Suez Canal Company—selaku pemegang otoritas Terusan Suez
sebelum dinasionalisasi oleh Presiden Nasser.
Pada dekade berikutnya, hubungan Israel
dengan negara-negara tetangga Arab tidak pernah sepenuhnya normal.
Menjelang Juni 1967, ketegangan antara Mesir dan Israel kembali
meningkat. Mesir memobilisasi pasukannya di sepanjang perbatasan Israel
di Semenanjung Sinai.
Sementara, Israel meluncurkan serangkaian
serangan udara terhadap lapangan udara Mesir pada 5 Juni. Peristiwa itu
menimbulkan Perang Arab-Israel Ketiga yang berlangsung selama enam
hari.
Dalam perang tersebut, Mesir juga dibantu
oleh sejumlah negara Arab lainnya, yaitu Yordania dan Suriah. Di
samping itu, Arab Saudi, Kuwait, Libya, Maroko, dan Pakistan juga ikut
mendukung Mesir dalam pertempuran tersebut.
Hasilnya, Mesir dan koalisi negara-negara
Arab kembali menelan kekalahan. Menurut catatan, ada sekitar 19 ribu
tentara Arab yang hilang atau gugur di medan perang kala itu.
Meski berulangkali menderita kekalahan,
upaya yang dilakukan Arab Saudi, Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan
Lebanon untuk membela Palestina di masa lalu menunjukkan betapa
tingginya rasa solidaritas mereka sebagai sesama bangsa Arab pada waktu
itu. Catatan sejarah tersebut menjadi ironis, mengingat hari ini
negara-negara Arab saling menuduh kafir dan memerangi saudara mereka
sendiri di Yaman.
(sumber: republika.co.id, Ikhwanul Kiram Mashuri, Ahmad Islamy Jamil, Nasih Nasrullah / berbagai sumber lain / edited: IndoCropCircles)






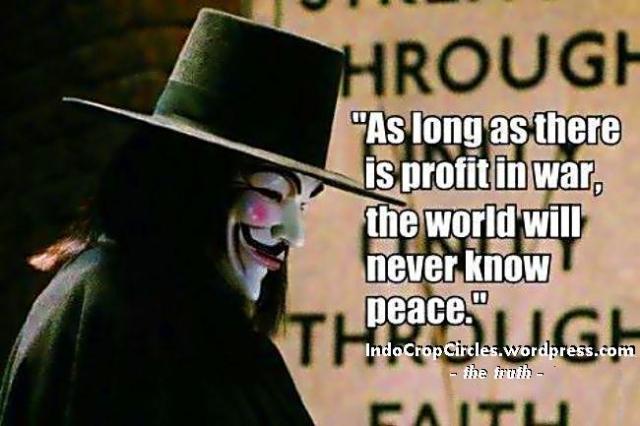

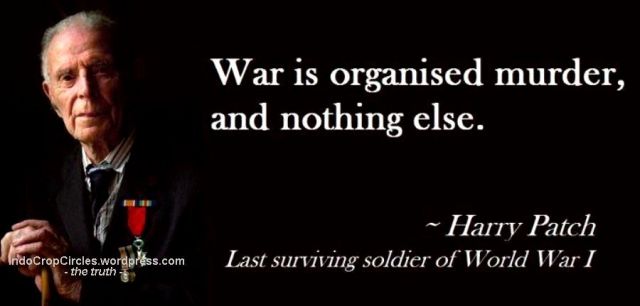










No comments:
Post a Comment